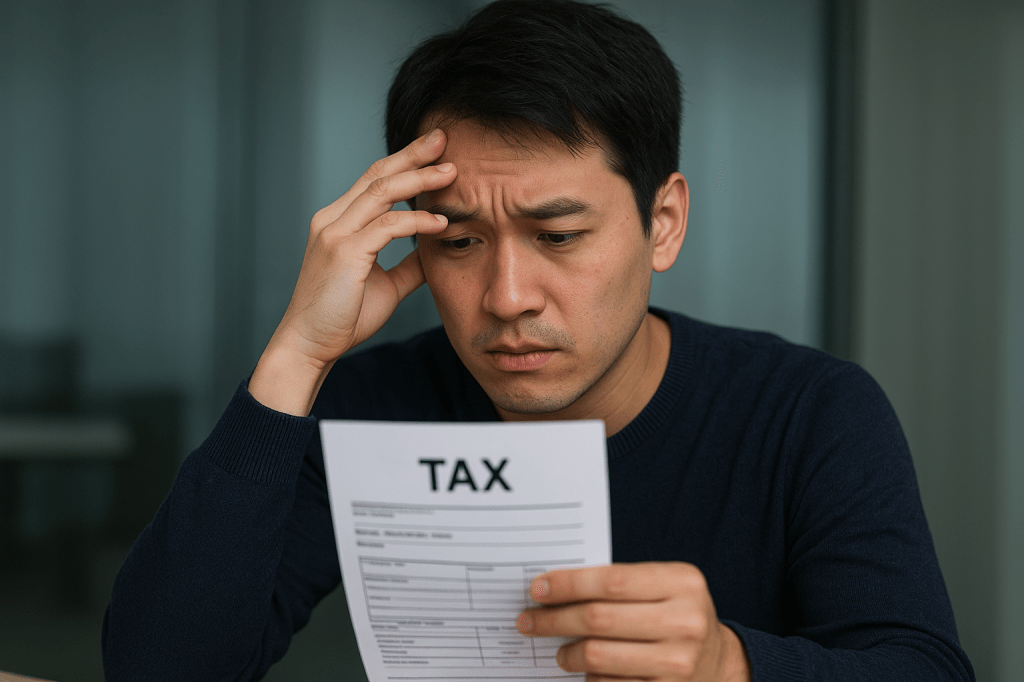Kemarahan publik terhadap kenaikan pajak sering dipandang sebatas penolakan spontan atas beban ekonomi. Padahal, yang sesungguhnya terjadi jauh lebih dalam: retaknya kontrak psikologis antara warga dan negara. Ketika pajak tak lagi dimaknai sebagai bentuk solidaritas, melainkan sebagai upeti yang dipungut sepihak, erosi kepercayaan publik menjadi tak terhindarkan.
Pajak sebagai Kontrak Psikologis
Dalam teori sosial-fiskal, kepatuhan pajak bukan hanya soal angka dan aturan, tetapi soal kepercayaan. Negara boleh memaksa, tetapi sejatinya efektivitas perpajakan bertumpu pada consent—persetujuan sukarela warga.
Kontrak psikologis pajak terbangun jika tiga unsur terpenuhi:
- Keadilan distributif → Warga merasakan manfaat nyata dari uang pajak.
- Keadilan prosedural → Prosesnya transparan, akuntabel, dan setara.
- Keadilan interaksional → Warga diperlakukan dengan hormat, bukan sebagai tersangka.
Sayangnya, wajah birokrasi perpajakan di Indonesia kerap dingin dan jauh dari empati. Banyak warga yang datang ke kantor pajak atau menghadapi razia merasa diperlakukan sebagai penjahat, bukan mitra. Perlakuan semacam ini meruntuhkan keadilan interaksional. Pajak pun kehilangan makna moralnya dan berubah menjadi hukuman sosial.

Spiral Ketidakpercayaan dan Resistensi
Kenaikan tarif tanpa perbaikan layanan publik memicu heuristik keadilan: orang langsung menyimpulkan sistem tidak adil, bahkan sebelum menghitung detail angka. Akibatnya, tax morale atau kepatuhan sukarela menurun drastis.
Inilah awal mula spiral ketidakpercayaan:
- Berawal dari keluhan kecil: “jalan kampungku tak pernah diperbaiki.”
- Berlanjut ke sinisme: “pajak hanya untuk mengisi kantong pejabat.”
- Lalu memuncak menjadi resistensi: penghindaran pajak, manipulasi laporan, atau penolakan terang-terangan.
Sayangnya, negara sering merespons fenomena ini dengan pengetatan aturan dan sanksi. Langkah koersif ini justru memicu psychological reactance—dorongan psikologis untuk melawan karena merasa otonomi dirampas. Alih-alih memulihkan legitimasi, pendekatan represif malah memperdalam jarak antara negara dan warganya.
Ketidaksetaraan, Populisme, dan Alienasi Politik
Masalah bertambah rumit ketika publik menyaksikan ketimpangan yang kasatmata:
- Pejabat dan pengusaha besar kerap lolos dari kewajiban pajak.
- Rakyat biasa justru dipaksa taat tanpa kompromi.
Ketidakadilan semacam ini menimbulkan kemarahan moral, bukan sekadar persoalan ekonomi. Warga bukan hanya merasa miskin, tetapi juga direndahkan martabatnya.
Di sinilah narasi populis menemukan momentumnya. Ketika kepercayaan pada institusi runtuh, pesan-pesan sederhana seperti “pajak Anda dicuri” atau “solusinya adalah pemimpin kuat yang berani menghapus pajak” jadi mudah diterima.
Lebih buruk lagi, alienasi fiskal bisa berkembang menjadi alienasi politik. Warga kehilangan rasa memiliki terhadap negara, menjadi apatis terhadap pemilu, skeptis terhadap partai, bahkan menolak negara sebagai rumah bersama. Krisis fiskal pun bertransformasi menjadi krisis demokrasi.
Jalan Keluar: Membalik Kontrak Psikologis
Mengatasi krisis ini tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan teknis menaikkan atau menurunkan tarif pajak. Yang diperlukan adalah transformasi relasi antara negara dan warganya. Ada tiga langkah strategis:
- Transparansi yang nyata
Negara harus menunjukkan secara jelas dan mudah diakses ke mana setiap rupiah pajak dibelanjakan. - Partisipasi publik
Bukan sekadar sosialisasi, tetapi konsultasi fiskal yang sungguh-sungguh melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. - Keteladanan elite
Penindakan tegas terhadap pengemplang pajak kelas atas akan lebih memulihkan kepercayaan publik dibandingkan seribu kampanye moral.
Pajak seharusnya menjadi simbol solidaritas sosial—bukan instrumen dominasi negara. Jika reciprocity ditegakkan, warga akan rela berkontribusi. Jika tidak, setiap kenaikan pajak hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Kepercayaan publik adalah modal psikologis kolektif yang rapuh. Sekali rusak, ia tak bisa dipulihkan dengan razia, denda, atau pidato teknokratik. Negara harus berhenti melihat warga sebagai sekadar pembayar pajak, dan mulai memperlakukan mereka sebagai mitra dalam kontrak sosial.
Jika negara gagal membalik kontrak psikologis ini, krisis fiskal hari ini hanyalah permulaan dari krisis demokrasi yang lebih besar di masa depan.